Konservasi: (Bukan) Basa-Basi?


“BUMI ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah” -Mahatma Gandhi.
Hari itu, Awang duduk bersantai di depan rumahnya. Usianya yang sudah mencapai angka 60 tahun, barangkali, selain menikmati masa senjanya yang tidak seindah puisi yang dibuat sambil menyeduh kopi dan mendengarkan lagu indie, tubuhnya yang sudah ringkih itu masih dipaksa untuk bekerja.
Matanya yang polos melambangkan kesahajaan, menyipit mengikuti gurat bibir yang selalu menyunggingkan senyum. Meskipun giginya sudah tidak ada lagi, senyum Awang selalu enak dilihat. Terlihat ketulusan di sana.


Awang merupakan salah seorang warga yang menempati Desa Pulau Cawan, salah satu pulau terbesar yang berada pada gugusan pulau lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Di pulau ini terdapat pantai berpasir yang terbentuk dari gerusan dan pecahan kerang sebagai sedimennya bernama Pantai Solop, yang demikian terkenal di Provinsi Riau hingga dijadikan salah satu lagu dan dinyanyikan langsung oleh Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.
Sehari-hari Awang berprofesi sebagai nelayan yang mengutip siput di sepanjang pesisir. Di lain hari, ia akan menjadi kuli di kebun kelapa milik seorang tuan tanah di desanya. Upahnya tak besar, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari, ia terpaksa harus mengutang di warung tetangga.
“Harga siput murah, Pak,” ujarnya singkat. Kemudian ia berkeluh kesah, “untuk makan sehari-hari kami hari berutang. Bahkan kalau sakit, kami ke Belaras.”
Ia kemudian menunjuk ke arah timur laut. “Sekalinya pergi ke Belaras, harus sewa boat, tidak kurang dari seratus ribu (rupiah). Kalau pakai sampan, belum sampai ke Belaras, kita sudah mati digulung gelombang,” ucapnya terkekeh.
Ucapannya diamini oleh istrinya yang dari tadi hanya mendengar dari dalam rumah. Ia keluar dan ikut menimpali perkataan suaminya.
“Mak sudah sakit dari lama. Kalau sudah kambuh, rasanya tak kuat mau ke mana-mana. Dulu, di sini ada bidan desa. Sekarang sudah tak ada lagi.”
Awang dan istrinya duduk bersejajaran. Muka yang hitam legam, lengan kurus, dan pandangan mata yang bersahaja itu terdiam beberapa saat.


Andai kata miskin boleh dilabeli kepada masyarakat yang mendiami suatu tempat sebagai stigma dan stereotip, maka barang tentu pilihan pertama yang menerima label tersebut adalah masyarakat nelayan.
Seakan miskin adalah pakaian sehari-hari, Awang dan istrinya menjalani hidup tanpa tahu bagaimana dan pada keturunan yang keberapa nasib mereka akan berubah.
Permasalahan kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh Awang saja. Berdasarkan data Direktorat Sekolah Dasar (Ditpsd) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022 sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir juga terkategori miskin.
Jumlah itu setara 12,5% dari total kemiskinan nasional sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan. Bahkan, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19%, atau lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 4%.
Yusmar Yusuf, seorang ahli fenomenologi Riau, menyebut bahwa nelayan hanya pelengkap halus dalam mesin besar peradaban pantai, yang berarti, sekapa apapun nelayan, ia tetap tidak bisa terlepas dari sangkaan peradaban miskin. Menurutnya lagi, tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi perkampungan nelayan selain dari nada falseto; sengau dan sumbang. Suasana bau pesing, kubang, ledah, dan kusam.
Hal ini tentu ironis, mengingat potensi dari laut yang demikian luas. Bahkan, Anwar dan Wahyuni, dalam tulisan mereka menulis dengan sangat apik mengenai kontradiksi ini pada tulisan berjudul Miskin di Laut yang Kaya. Nelayan Indonesia dan Kemiskinan menyimpulkan, setidaknya ada dua kesimpulan mengenai permasalahan kemiskinan, antara lain: kemampuan modal yang lemah, dan terkait kebijakan pemerintah.
Menurutnya lagi, kemampuan modal yang lemah menjadi penyebab utama dari kemiskinan nelayan. Berangkat dari hal tersebut, dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk “bermain” harga jual ikan, sehingga nelayan kecil selalu dalam keadaan terlilit utang.
Selain itu, perlu diakui jua bahwa terbatasnya kemampuan olah produk perikanan berimbas pada daya serap industri pengelolaan ikan yang terbatas. Tidak selesai di situ saja, nelayan Indonesia juga dihadapkan pada persaingan dengan nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal dan mempunyai kekuatan armada yang lebih canggih.
Untuk itu, perlu adanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah—yang dirasa belum berpihak kepada mereka dalam daya saing antara nelayan kecil dan tradisional—dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan dengan cara pembangunan terpadu pada kawasan pesisir, dan melakukan kerja sama dengan semua pihak, paling penting dengan melibatkan nelayan dalam pembangunan kawasan pesisir.
Menjawab kerisauan tersebut, setidaknya, pada tahun 2007, pemerintah Republik Indonesia (mencoba) menunjukkan keseriusannya dalam hal pengelolaan ruang laut dengan menelurkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundangan ini sejalan dengan “kakaknya” UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pada UU No. 26 Tahun 2007, ruang dibahasakan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.
Kompleksnya pengertian ruang dan juga pemanfaatannya membuatnya penting untuk dilakukan penataan dan pengelolaan.
Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Untuk menciptakan hal tersebut, maka perlu memerhatikan aspek-aspek antara lain: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.
Maka, untuk mewujudkan hal tersebut, secara spesifik, terkait dengan penataan dan pengelolaan ruang laut, kemudian diterjemahkan lebih lanjut pada UU Nomor 27 tahun 2007.
Pada Undang-undang ini, pemerintah daerah diamanatkan untuk membuat Rencana Tata Tuang Wilayah (RTRW) khusus kawasan laut yang dikenal dengan nama Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi dan Kabupaten. Hingga kemudian, pada tahun 2014, lahir sebuah regulasi baru yang mengubah wajah kelautan Indonesia.
Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menyebabkan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang semula 0 sampai 4 mil yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan pengelolaan laut di atas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, menjadi kewenangan provinsi secara penuh.
Pada undang-undang ini, sektor kehutanan dan kelautan ditarik menjadi pengelolaan provinsi. Artinya, pengelolaan ruang laut jarak 0 hingga 12 mil (di luar minyak dan gas bumi) menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam sub sektor kehutanan dan kelautan.
Hal ini tentu berimplikasi kepada terbengkalainya segala urusan pengelolaan laut, terutama pada kawasan kabupaten/kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut/pulau. Namun demikian, ada baiknya juga segala pengurusan terpusat pada pemerintah provinsi agar semua lebih terarah dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Prinsipnya, penyusunan RZWP3K harus mempertimbangkan asas: keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung, ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir.
Selain itu wajib juga mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Serupa dengan RTRW Daerah, RZWP3K harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang berlaku selama 20 tahun namun dapat ditinjau kembali dalam 5 tahun.
Produk dari RZWP3K berupa dokumen yang setidaknya memuat pengalokasian ruang (kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut); keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion; penetapan pemanfaatan ruang laut; dan penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri stategis, serta pertahanan dan keamanan nasional.
Kemudian, UU Nomor 27 tahun 2007 ini bertransformasi menjadi UU No. 1 Tahun 2014 yang mana terdapat perubahan pada beberapa poin, seperti pada pasal 17 UU Nomor 27 Tahun 2007 diubah dengan menyatakan bahwa bahwa RZWP3K menjadi dasar pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan alokasi dan peruntukan ruang tersebut.
Secara perlahan, satu per satu provinsi mulai menyelesaikan rumusan RZWP3K. Berdasarkan keterangan tertulis Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL, KKP-RI, pada tahun 2020 telah ditetapkan Perda RZWPK3 sebanyak 27 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia (saat ini sudah menjadi 38 provinsi).
Perjalanan panjang penataan ruang laut tidak berhenti pada RZWP3K saja. Merujuk pada Menata Ruang Laut Indonesia terbitan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inverstasi (Kemenkomarves), disebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 alasan pokok yang menyebabkan upaya pengelolaan laut merupakan suatu kebutuhan.
3 alasan tersebut adalah sebagai berikut: Adanya penguasaan, hak, dan wewenang menurut batas-batas ruang yang telah ditetapkan di laut bagi pihak tertentu sebagai subjek pengelolaan; adanya ragam sumber daya dan jasa lingkungan laut yang membutuhkan ragam perlakuan sebagai objek pengelolaan; serta adanya ukuran keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola laut sebagai predikat pengelolaan.
Rumusan pengelolaan laut yang tidak kalah penting adalah adanya kawasan konservasi, baik daerah maupun nasional. Penetapan suatu kawasan laut menjadi kawasan konservasi selayaknya tidak serta-merta terjadi begitu saja.
Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi seyogyanya adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dalam pengelolaannya, kawasan konservasi dibagi berdasarkan zonasi yang merupakan batas-batas fungsional di kawasan konservasi, yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
Dalam pengelolaannya, diperlukan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, yaitu dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi, dan berdasarkan kajian serta pembahasan berlapis.
Saat ini, kawasan konservasi laut di Indonesia sudah mencapai luas 28,4 juta ha, dengan luas area zona inti mencapai 0,5 juta ha, atau sekitar 87% dari target seluas 32,5 juta ha pada tahun 2030 mendatang. Bahkan, tidak main-main, secara ambisius, pemerintah menargetkan 30% dari luas laut Indonesia merupakan kawasan konservasi, yang sedikitnya luasan kawasan konservasi mencapai 9,75 juta hektare pada 2045 mendatang.
Target ini seakan menjawab tantangan dari konvensi internasional, di mana menetapkan sekitar 10 persen kawasan laut Indonesia harus mendapat perlindungan untuk melestarikan fungsi ekosistemnya.
Pemerintah Indonesia tentu boleh berbangga hati, sebab target tersebut menjadi relevan dengan pencapaian yang sudah diraih Indonesia untuk poin 14 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Aichi Target. Lebih jauh, diharapkan nanti juga bisa menopang Indonesia dalam Net Sink dan mengimplementasikan blue carbon dan blue economy.
Poin terakhir ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa program prioritas digalakkan pemerintah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti swasembada garam, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengembangan pariwisata bahari, serta pembangunan-pembangunan prasarana bawah laut yang keseluruhannya membutuhkan alokasi ruang.
Dengan adanya alokasi ruang (baik itu peruntukannya bagi peningkatan infrastruktur, ekonomi, maupun untuk konservasi) diharapkan tidak ada gap antara ekologi dan ekonomi sesuai dengan cita-cita pemerintah menjadi poros maritim dunia.
Ditunjang juga dengan 3 pilar pembangunan yang meliputi: pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, bisa diterjemahkan sebagai pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Dengan demikian, konsep kawasan konservasi dirasa merupakan pilihan yang tepat saat ini, mengingat pada kawasan konservasi juga mengakomodasi kearifan lokal, yang merupakan nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Kendati demikian, kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan di atas, bukan berarti melarang segala aktivitas di dalamnya, melainkan mengatur berdasarkan alokasi ruang berdasarkan rencana pengelolaannya, dan juga tentu berinduk kepada RZWP3K.
Namun, bukan berarti niat baik pemerintah dengan mencetuskan kawasan konservasi tersebut tidak mendapat tentangan yang sebenarnya lebih kepada pertanyaan mengenai dampak dari berbagai kebijakan yang dibenturkan.
Semisal, target untuk melindungi laut dengan pencetusan kawasan konservasi, dan di satu sisi memberikan izin untuk investasi memanfaatkan ruang laut melalui penerbitan izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Yang lebih membuat tercengang lagi, terbitnya PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Kejadian ini tentu membuat hantaman besar bagi pemerintah Indonesia, dan dipertanyakan kembali komitmennya mengenai keseriusan dalam mengelola kawasan konservasi.
Pemerintah dianggap terkesan mencoba memaksakan adanya perkawinan antara nilai ekologi dan ekonomi. Akibatnya, konservasi yang sudah dilakukan hanya terkesan basa-basi.
Berdasarkan pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, “Dapatkah konservasi dan investasi disandingkan?”
Di level terbawah semisal pemerintah desa, kejadian seperti ini juga sering terjadi. Mengambil contoh, di sebuah desa Provinsi Riau, tempat yang tengah diinisiasi menjadi Kawasan Konservasi Daerah, terdapat panglong (tungku pengolahan) arang bakau milik salah pejabat desa tersebut. Hal ini tentu ironi, mengingat di desa tersebut juga terdapat sebuah peraturan desa yang melarang menebang mangrove sepanjang kawasan tersebut.
Seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahkan berkata dengan nada sinis, “Awak (kami) di sini menjaga, yang di ujung tukang binasa. Jadi kami bisa apa?”
Senada, Awang, lelaki tua itu menutup percakapan siang itu dengan sebuah pernyataan ketika ditanyakan mengenai pentingnya menjaga laut melalui pencadangan kawasan konservasi laut di daerahnya.
“Laut itu tak perlu kita jaga, Pak. Tidak akan terjaga oleh kita laut yang sedemikian luas itu,” ujarnya mantap. Dia kembali tersenyum, namun kali ini senyumnya begitu susah untuk diartikan. Entah bermakna sinis, entah pesimis.
Terlepas dari kontroversi, dan tudingan sana-sini, tentu kita sama-sama yakin dan percaya, prinsip konservasi yang digaungkan pemerintah serupa iklan rokok tahun 90-an, “Bukan basa-basi”. Ya, semoga. ***
Baca juga: IUU Fishing: Kejahatan Lintas Negara Yang Terorganisir, Berbahaya, Dan Serius
Editor: J. F. Sofyan
Sumber:
Sumber jurnal:
Anwar, Z dan Wahyuni. 2019. Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. Vol. 4 No. 1 (2019): Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
Sumber buku:
Deputi Sumber Daya Maritim. 2021. Menata Ruang Laut Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Yusuf, Y. 2015. Nelayan dan Laut dalam Melayu, Langit dan Kimia Darat. Jakarta; Penerbit Wedatama Widya Sastra.
Sumber internet:
https://setkab.go.id/rzwp-3-k-kepastian-hukum-bagi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/ diakses pada 5 Juni 2023 pukul 21.03 WIB.
https://www.icctf.or.id/kkp-sebanyak-27-provinsi-telah-tetapkan-perda-zonasi-pesisir/#:~:text=%E2%80%9CPada%20tahun%202020%20telah%20ditetapkan,yang%20diterima%20di%20Jakarta%2C%20Selasa. diakses pada 6 Juni 2023 pukul 10.01 WIB.
Ambari. 2022. 22 Tahun Lagi, 30 Persen Laut adalah Kawasan Konservasi. https://www.mongabay.co.id/2022/12/13/22-tahun-lagi-30-persen-laut-adalah-kawasan-konservasi/ diakses pada 7 Juni 2023 pukul 11.26 WIB.
https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/ diakses pada 7 Juni 2023 pukul 11.32 WIB.
https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/5543/manfaat-ganda-kawasan-konservasi-laut?lang=1 diakses pada 7 Juni 2023 pukul 13.14 WIB.
Sumber regulasi:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan







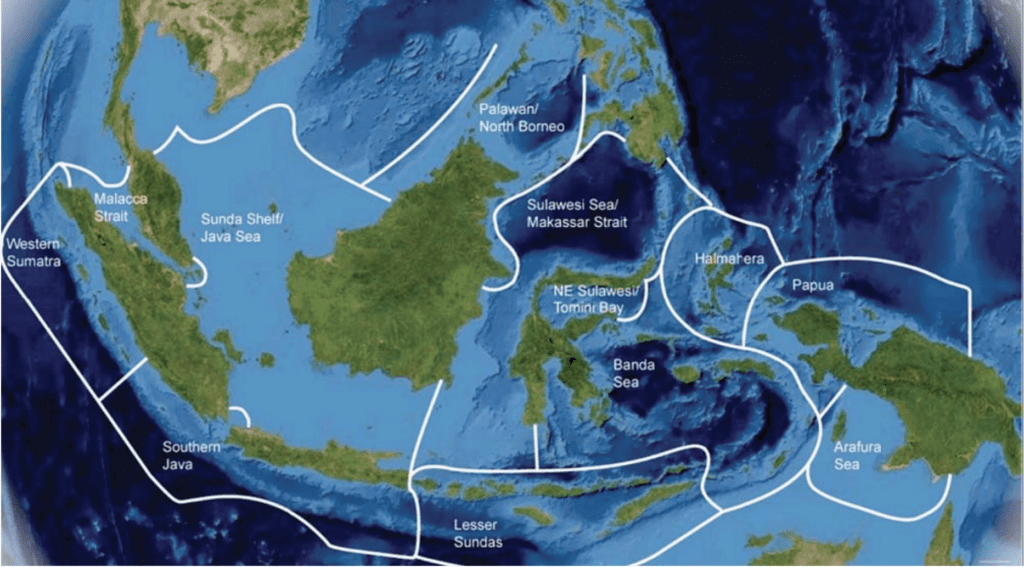

Tanggapan